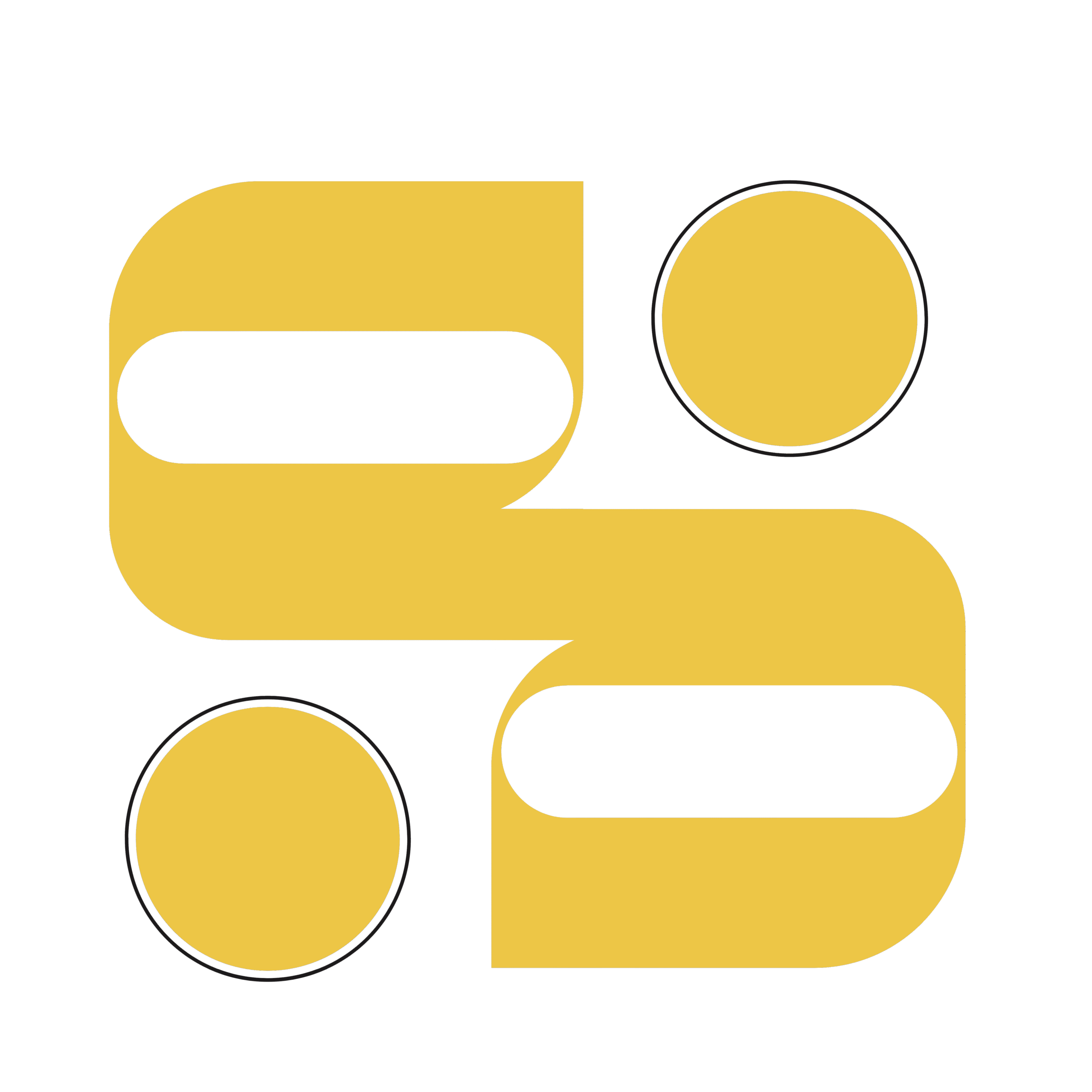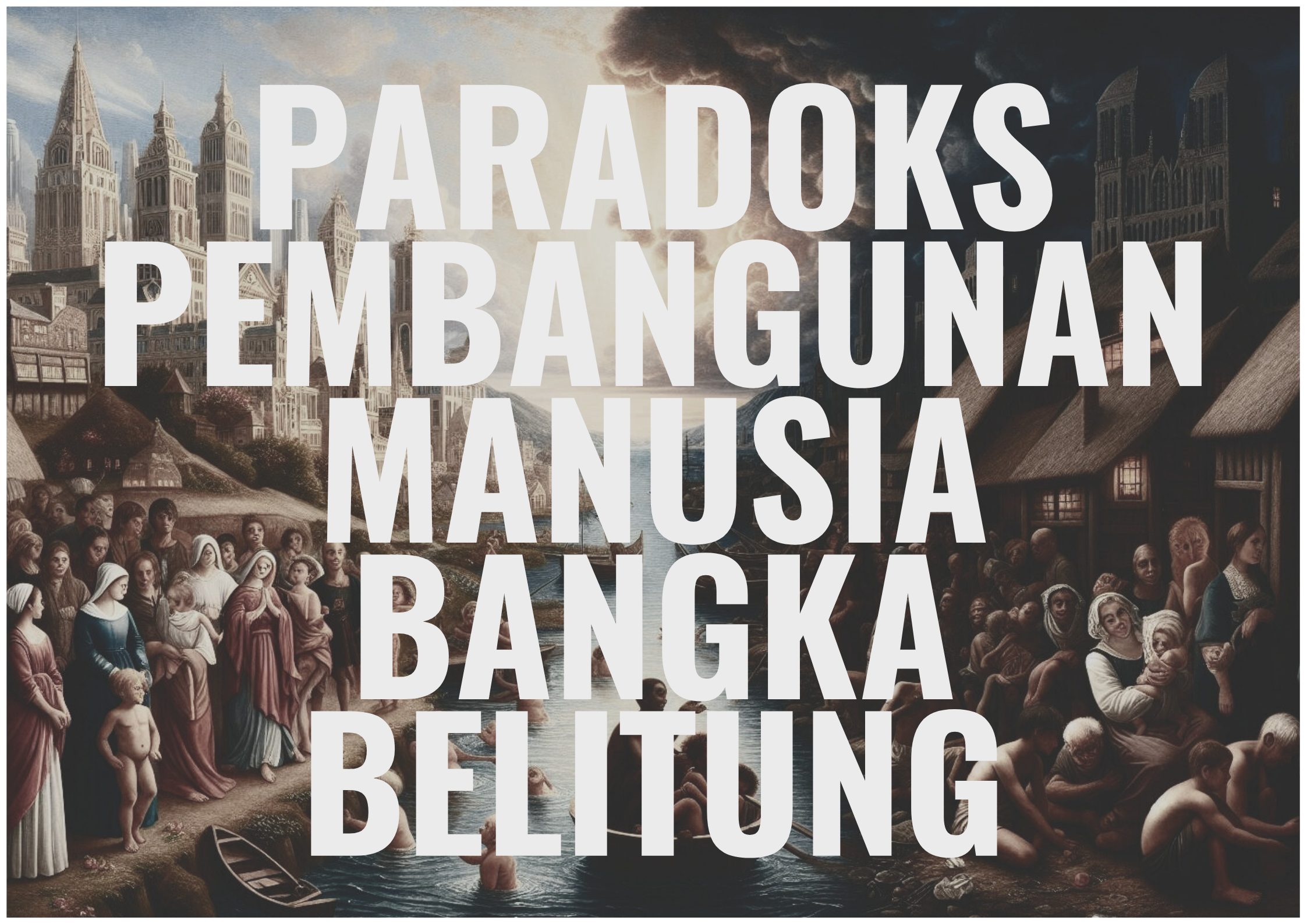Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah lama digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pembangunan suatu wilayah. IPM menggabungkan tiga dimensi fundamental: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat capaian IPM sebesar 73,33, yang menempatkannya dalam kategori “tinggi”. Angka ini sekilas menunjukkan bahwa pembangunan manusia di provinsi ini berada pada jalur yang cukup baik. Namun, jika data ini diurai ke tingkat kabupaten dan kota, muncul sebuah paradoks: capaian rata-rata yang tampak menggembirakan ternyata menyembunyikan kesenjangan serius antarwilayah.
Rata-rata yang Menyembunyikan Kesenjangan
Perbandingan antardaerah mengungkap disparitas yang mencolok. Kota Pangkalpinang mencatat IPM tertinggi dengan 80,40, sejalan dengan capaian harapan lama sekolah (HLS) yang juga tertinggi, yakni 13,30 tahun. Sebaliknya, Kabupaten Bangka Selatan mencatat IPM hanya 68,86 dengan HLS 11,71 tahun, yang berarti tertinggal lebih dari satu setengah tahun dibandingkan Pangkalpinang. Kabupaten Bangka Barat juga menunjukkan capaian relatif rendah, dengan IPM 70,67.
Kontras ini memperlihatkan bahwa capaian rata-rata provinsi dapat menyesatkan jika tidak disertai analisis distribusi. Secara statistik, rata-rata memang mengangkat nilai agregat, tetapi pada saat yang sama berpotensi menutupi kesenjangan internal. Analogi sederhananya, sebuah kelas dapat memiliki nilai rata-rata tinggi meskipun sebagian besar siswanya gagal, karena ada beberapa siswa yang nilainya sangat baik. Fenomena inilah yang sedang terjadi di Bangka Belitung.
Implikasi Ketidakmerataan
Ketimpangan capaian pembangunan manusia tidak berhenti pada angka statistik, tetapi memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang nyata. Pertama, akses pendidikan yang timpang berdampak pada peluang kerja dan pendapatan. Daerah dengan harapan lama sekolah yang lebih rendah cenderung menghasilkan angkatan kerja dengan keterampilan terbatas, sehingga peluang ekonomi mereka menyempit.
Kedua, kesenjangan kesehatan juga berimplikasi pada produktivitas jangka panjang. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik di kota besar, seperti Pangkalpinang, menciptakan jurang kualitas layanan dibandingkan kabupaten dengan infrastruktur terbatas.
Ketiga, fenomena urbanisasi dan brain drain tidak terelakkan. Masyarakat muda dari kabupaten dengan capaian IPM rendah cenderung bermigrasi ke pusat kota untuk mencari pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya, daerah tertinggal kehilangan potensi sumber daya manusia terbaik, sehingga memperparah lingkaran ketidaksetaraan.
Faktor Penyebab
Disparitas pembangunan di Bangka Belitung tidak terjadi tanpa sebab. Pertama, terdapat sentralisasi pembangunan di Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi. Konsentrasi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja secara alamiah menarik investasi dan SDM ke pusat kota, sementara daerah lain tertinggal.
Kedua, masih kuatnya ketergantungan ekonomi pada sektor tambang timah dan sektor informal membatasi diversifikasi ekonomi di tingkat kabupaten. Ketika basis ekonomi tidak kokoh dan tidak beragam, investasi pada pendidikan dan kesehatan cenderung tidak menjadi prioritas.
Ketiga, terdapat kesenjangan dalam distribusi kebijakan publik. Program pembangunan seringkali lebih mudah terealisasi di daerah dengan infrastruktur dasar yang memadai, sehingga daerah yang sudah maju semakin maju, sedangkan yang tertinggal semakin terpinggirkan.
Pertanyaan Kritis: Pembangunan untuk Siapa?
Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pembangunan manusia di Bangka Belitung benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, ataukah sekadar menghasilkan angka statistik yang baik di tingkat provinsi? Jika pembangunan hanya mengejar capaian rata-rata, maka orientasi kebijakan hanyalah gincu: sejenak terlihat indah di laporan nasional, tetapi tidak menyentuh masalah struktural di lapangan.
Ketidaksetaraan pembangunan manusia bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan keadilan sosial. Daerah yang tertinggal dalam pendidikan dan kesehatan pada akhirnya akan menghadapi kerentanan sosial yang lebih besar, mulai dari kemiskinan antargenerasi, rendahnya partisipasi ekonomi, hingga lemahnya daya saing wilayah.
Jalan ke Depan: Pemerataan sebagai Agenda Utama
Untuk keluar dari paradoks ini, diperlukan kebijakan yang menekankan pada pemerataan pembangunan. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan dan para elit politik antara lain:
- Peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten tertinggal, bukan hanya memperpanjang lama sekolah, tetapi memastikan mutu pengajaran dan akses setara ke sarana pendidikan modern.
- Penguatan layanan kesehatan dasar melalui distribusi tenaga medis yang lebih adil dan peningkatan fasilitas di daerah terpencil.
- Diversifikasi ekonomi lokal, agar kabupaten tidak hanya bergantung pada tambang atau sektor informal, tetapi mampu mengembangkan pariwisata, pertanian berkelanjutan, dan industri kreatif.
- Kebijakan afirmatif berbasis data, di mana daerah dengan capaian IPM rendah diberi prioritas program pembangunan, alih-alih mendapatkan porsi anggaran yang sama rata.
Penutup
Paradoks pembangunan manusia di Bangka Belitung menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat diukur hanya dari rata-rata provinsi. Ketimpangan antardaerah perlu diakui sebagai masalah serius yang harus dijawab dengan kebijakan yang lebih inklusif dan distributif. Pembangunan yang adil bukan berarti setiap daerah harus memiliki capaian yang sama, tetapi setiap masyarakat di setiap kabupaten memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang.